
Summer School PERSETIA, berlangsung pada tiga hingga sebelas Agustus 2025. Dengan mengusung tema Pendampingan dan Konseling Pastoral di Era Disrupsi, seluruh kegiatan berlangsung di STT HKBP Pematang Siantar, yang didapuk menjadi tuan dan nyonya rumah sejak RUA PERSETIA di Sumba. Summer School kali ini, didampingi oleh dua Project Officers, yakni Pdt. Arni Dangga Mesa, M.Th., dan Prof. Rachel Iwamony, Ph.D.
Ada 37 orang mahasiswa pascasarjana yang mengikuti kegiatan ini, mereka datang dari 17 Sekolah Tinggi Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Kristen, dan Fakultas Teologi. Ada dua dosen pengampu dan satu pembicara yang mendampingi mahasiswa peserta Summer School.

Dua dosen pengampu Melinda Siahaan, Ph.D., dan Dr. Alokasih Gulo, M.Si., memberikan materi terkait Pendampingan dan Konseling Pastoral di Era Disrupsi. Selain itu, Dr. Jordan Humala Pakpahan, juga menjadi narasumber yang berkesempatan menyampaikan materi yang bertajuk “Praxis Penyembuhan Subjek Tertindas, Memahami Subjek yang Merdeka dari perspektif Psikoanalisa yang Membebaskan, dan kegunaanya untuk terapi kesembuhan.”
Melinda Siahaan, Ph.D., mengangkat urgensi pelayanan pastoral di tengah era disrupsi sosial dan teknologi yang kian kompleks. Sebelum masuk dalam pembahasan inti, Ia menelisik pengertian disrupsi. Disrupsi, dalam pemaparan Siahaan, kini menjadi simbol perubahan besar dalam tatanan masyarakat akibat inovasi teknologi dan pergeseran nilai.
Disrupsi teknologi mempengaruhi industri, relasi sosial, hingga norma moral. Francis Fukuyama, yang digunakan oleh Siahaan dalam membangun argumentasinya, menyebut “The Great Disruption” sebagai masa meningkatnya kejahatan, runtuhnya kohesi sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap Institusi. Disrupsi juga akhirnya memberikan dampak seperti kemiskinan, kebijakan publik yang keliru, pergeseran budaya, dan krisis keluarga.
Dengan kondisi seperti ini, dalam amatannya, Siahaan memberikan tawaran. Modal sosial seperti kepercayaan dan norma informal menjadi penyeimbang penting dalam menghadapi disrupsi. Beranjak dari tawaran ini, Siahaan selanjutnya menandaskan bahwa pendampingan komunitas, konseling interkultural, pendampingan keluarga, dan konseling intergenerasi sangat dibutuhkan. Modal sosial inilah yang menjadi penggerak dan fondasi utama dalam membangun tatanan hidup, dengan mengandaikan masyarakat bisa saling mempercayai. Di titik inilah teologi bisa mengambil peran, memberikan pendampingan bagi mereka yang mengalami “guncangan” tersebut.
***
Gereja telah cukup lama mewarisi model klasik yang bertumpu pada otoritas pendeta dan ajaran teologi yang “mapan.” Gereja kini ditantang untuk berhadapan dengan realitas baru. Disrupsi digital, trauma kolektif, dan pergeseran makna iman, menantang gereja untuk menemukan mode-model dalam pendampingan dan konseling pastoral.
Pdt. Dr. Alokasih Gulo, dosen pendamping dalam Summer School, menandaskan bahwa tidak ada model tunggal yang cukup. Model-model seperti model klasik, naratif, komunitarian, dan holistik, adalah tradisi yang perlu dipadukan dan dikembangkan sesuai dengan konteks masing-masing.
Gulo juga berargumen bahwa model klasik memberi kepastian arah moral, tetapi kerap terasa kaku dan hierarkis. Model naratif membuka ruang bagi jemaat untuk menyulam kembali makna hidup melalui kisah dan luka yang dibagikan. Model komunitarian menghidupkan semangat gotong royong, sementara model holistik menekankan tubuh, jiwa, emosi, hingga ekologi sebagai satu kesatuan yang harus dirawat. Semua model-model tersebut, memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri, tetapi tak cukup untuk menjawab tantangan dan realitas zaman.
Era disrupsi menghadirkan realitas baru: ibadah berpindah ke layar, perjumpaan tatap muka digantikan ruang virtual, krisis keintiman rohani muncul di tengah budaya instan, sementara pandemi memperdalam luka mental jemaat. Maka muncullah gagasan empat model inovatif, yang diramu dari empat model tersebut. Tujuannya menjembatani jurang antara tradisi, realitas masa kini, dan masa depan. Selain menyampaikan materi, dua dosen pendamping, juga melakukan coaching terhadap seluruh mahasiswa, secara khusus dalam penulisan artikel. Mahasiswa didampingi, agar tulisan-tulisan mereka bisa dikirimkan ke jurnal bereputasi.
***
Kehidupan manusia di era disrupsi ditandai oleh percepatan teknologi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi yang mengubah pola kerja serta relasi sosial. Dampak yang muncul bersifat ganda: teknologi bisa menjadi berkat, namun juga membawa malapetaka. Kompetisi manusia dengan robot telah memicu pengangguran massal, memperlebar jurang ketidaksetaraan, dan melahirkan penyakit mental dalam skala luas. Bukan hanya kalangan miskin yang terdampak, bahkan mereka yang religius pun tak jarang terjerat depresi, kekerasan, atau perilaku menyimpang.
Kapitalisme neoliberal menghadirkan wajah baru perbudakan. Kebebasan yang diagungkan justru menjelma sebagai paksaan halus yang membuat individu menjadi budak bagi dirinya sendiri. Setiap orang dituntut untuk terus mengeksploitasi tubuh dan pikirannya tanpa henti. Kapitalisme melahirkan masyarakat yang lelah, teralienasi, dan resah. Akibatnya, subjek manusia terseret ke dalam lingkaran depresi, stres, bahkan keputusasaan ekstrem seperti bunuh diri. Penindasan yang dialami tidak hanya bersifat material, melainkan juga psikologis. Trauma kolonial dan ketidakadilan struktural menanamkan rasa inferioritas dan kebingungan identitas yang diwariskan lintas generasi, hingga membentuk norma penindasan yang diterima tanpa sadar.
Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan dialog lintas disiplin antara teologi, psikologi, dan psikoanalisis. Sejak awal, psikoanalisis lahir dari pengalaman kaum Yahudi yang tertindas di Eropa, sehingga memiliki akar pembebasan. Pemikiran Freud, Fanon, dan Freire menunjukkan bahwa luka psikologis manusia tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang menindas. Di Amerika Latin, Ignacio Martín-Baró mengembangkan psikologi pembebasan untuk merespons realitas opresi politik dan ekonomi, sebuah tradisi yang kini dilanjutkan oleh pemikir kontemporer seperti Daniel Gaztambide dan Robert Beshara. Gaztambide menekankan perlunya dekolonisasi dengan melucuti warisan kolonial dan kapitalisme rasial, sementara Beshara menawarkan psikoanalisis kontrapuntal yang memadukan Freud dan Edward Said untuk membaca kekerasan sistemik dan membuka ruang bagi subjektivitas pembebasan.
Bagi Dr. Jordan Humala Pakpahan, penyembuhan ini tidak hanya soal teori psikologis, melainkan juga panggilan iman. Gereja, katanya, tidak boleh berhenti pada penghiburan rohani semata. Praxis penyembuhan harus dipahami sebagai Kristopraxis, yakni melanjutkan karya Kristus yang membebaskan manusia dari dosa sekaligus dari penindasan sosial. Keselamatan bukan hanya pembebasan spiritual, tetapi juga sosial, material, dan struktural.
Dalam kerangka praktis, penyembuhan diwujudkan melalui dialog terapeutik, transferensi, interpretasi narasi, dan revisi identitas melalui pengampunan. Namun, terapi tidak boleh berhenti di ruang konseling. Ia harus bergerak menuju aksi politik, kesadaran kritis, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Dekolonisasi, perlawanan terhadap rasisme dan kapitalisme, hingga upaya mempersoalkan kembali hal-hal yang dianggap “alami” menjadi bagian dari strategi penyembuhan yang sejati.
Di tengah dunia yang sarat luka akibat disrupsi dan kapitalisme, praxis penyembuhan hadir sebagai jalan alternatif: menghubungkan iman, psikologi, dan perjuangan sosial. Gereja dipanggil untuk tidak sekadar mengobati gejala, melainkan juga menyentuh akar-akar opresi yang membuat manusia sakit. Dengan demikian, penyembuhan menjadi sebuah gerakan yang melampaui ruang batin, merambah ke ranah sosial dan politik, hingga akhirnya menjadi upaya nyata untuk membangun kemanusiaan yang lebih adil.
Selain di dalam kelas, peserta Summer School juga berkesempatan melakukan studi lapangan. KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) dan Panti Asuhan Elim, menjadi tempat dan ruang memberi serta belajar bagi seluruh peserta. Di KSPPM misalnya, peserta diajak untuk melihat sejauh mana alam dieksploitasi. Peserta juga diajak untuk melihat advokasi yang bisa dilakukan ke depan, sebagai pemimpin umat dan kelompok intelektual. Di kesempatan itulah, para peserta melakukan “pastoral investigatif,” gagasan yang ditawarkan oleh John Campbell.
Mahasiswa melakukan pengamatan atas apa yang terjadi pada alam. Mereka juga melakukan refeleksi atas apa yang mereka lihat, dan memberikan tesis preskriptif—yang berisis tawaran dan rekomendasi praktis atas apa yang mereka lakukan.

Kunjungan mahasiswa ke Panti Asuhan Elim HKBP, juga dilakukan pada hari Minggu, 10 Agustus 2025. Dalam kunjungan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk mendengar pemaparan pengelola PA Elim, sebelum seluruh peserta berkesampatan untuk bersua dan mendengarkan cerita dari anak-anak yang ada di sana. Kesempatan ini, menjadikan mahasiswa, tidak hanya sekadar datang dan memberikan sesuatu, lalu mengambil gambar. Mahasiswa juga diajak untuk belajar dan mendengarkan cerita anak-anak.
Kegiatan ini, bisa terlaksana oleh dukungan banyak pihak. Pertama oleh sekolah-sekolah anggota, kedua oleh STT HKBP, yang adalah nyonya/tuan rumah, serta Mission-21 yang menjadi mitra dalam kegiatan ini. Saat kegiatan ini ditutup pada tanggal 10 Agustus, ada sebuah pergumulan dan harapan yang muncul. Pergumulan, karena pendampingan dan konseling pastoral, dibutuhkan bukan hanya pada gereja dan masyarakat, tetapi juga untuk keutuhan semesta. Namun, harapan juga tetap tumbuh. Ada 37 mahasiswa yang siap kembali ke konteks mereka masing-masing, dan menjadi agen-agen perubahan.
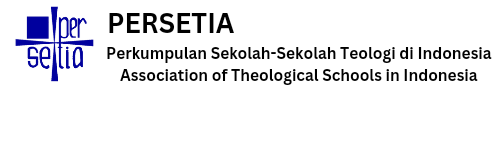
Be the first to comment